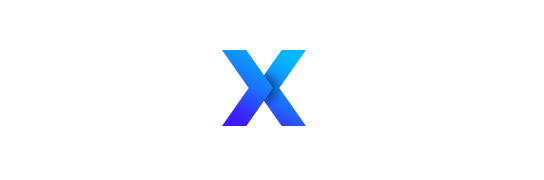Jakarta, Malanesianews, – Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KIARA), Susan Herawati, menyoroti bahwa orientasi utama Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30) di Belem, Brasil, masih berpusat pada realisasi pendanaan iklim dari negara-negara maju. Perkembangan ini sejalan dengan usulan tuan rumah COP30, Brasil, bersama Azerbaijan (COP29) melalui Baku to Belem Roadmap to USD 1,3 Triliun, yang bertujuan memobilisasi pembiayaan iklim tahunan bagi negara berkembang. Namun, KIARA berpandangan bahwa titik tekan negosiasi di panggung global hanya berkutat pada pendanaan dan carbon trading, tanpa menyentuh inti permasalahan, yakni menekan masifnya aktivitas industri ekstraktif dan eksploitatif yang merupakan kontributor emisi terbesar.
Fokus negosiasi yang tidak menyentuh akar masalah ini berkonsekuensi langsung pada berulangnya seremonial iklim tanpa adanya pengurangan produksi emisi korporasi multinasional, serta semakin masifnya eksploitasi sumber daya alam. Di tengah dorongan pendanaan iklim yang diklaim akan disalurkan kepada masyarakat, KIARA mencatat realitas yang kontradiktif, di mana Indonesia masih menempati peringkat keenam sebagai negara penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia pada tahun 2024. Ironisnya, alih-alih perlindungan, wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, terutama di Indonesia Timur yang kaya sumber daya, justru menghadapi ancaman yang diperparah.
Ancaman ini termanifestasi dalam peningkatan tajam industri ekstraktif seperti pertambangan nikel, pertambangan pasir laut, dan alih fungsi mangrove. Kegiatan-kegiatan ini, yang banyak terjadi di wilayah-wilayah seperti Sulawesi, Maluku, dan sekitarnya di Indonesia Timur, menyebabkan hilangnya ruang kelola masyarakat dan kerusakan parah ekosistem pesisir. Susan Herawati secara tegas menyebut fenomena ini sebagai Ocean Grabbing, di mana ruang kelola masyarakat dirampas. Menurutnya, realitas di lapangan, khususnya di wilayah pesisir timur, sangat bertolak belakang dengan narasi perlindungan yang dibawa oleh delegasi pemerintah di tingkat internasional.
Lebih lanjut, Susan menilai proyek-proyek mitigasi dan pendanaan iklim yang ada belum bersifat protektif bagi ekosistem esensial. Proyek mitigasi seperti Giant Sea Wall atau perdagangan karbon dianggap sebagai solusi palsu. Bahkan, perlindungan ekosistem vital seperti mangrove, terumbu karang, dan lamun di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil Indonesia dinilai minim, terutama karena Pemerintah Pusat maupun Daerah tidak memiliki data existing yang valid mengenai luasan ekosistem tersebut. Hal ini memperjelas bahwa “bahan jualan karbon” pemerintah di forum internasional berpotensi besar menjadi solusi palsu untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, terutama bagi masyarakat pesisir di Indonesia Timur yang paling rentan terdampak.